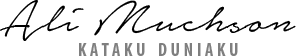Mental Korupsi dari Balik “Hedonic Treadmill”
SURABAYA – Kita tumbuh dalam narasi bahwa sukses adalah segalanya, hidup baru bernilai jika dipenuhi pencapaian. Bahwa bahagia akan datang setelah gelar, jabatan, berpengaruh, dan pundi-pundi telah menggunung. Namun, mengapa justru banyak yang telah sampai di “puncak” itu merasa hampa, kehilangan arah, bahkan tak tahu lagi apa yang sebenarnya mereka dikejar.
Dalam dunia yang terus memacu kita untuk berlari lebih cepat, mungkin inilah saatnya kita bertanya, “Apakah kita sungguh berlari menuju bahagia, atau justru terjebak dalam lintasan yang akan justru benar-benar membawa kita ke jalan menistakan diri sendiri?”
Dalam pandangan umum, kesuksesan kerap dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kualitas hidup seseorang. Gelar akademis, karier cemerlang, rumah megah, dan saldo tabungan dianggap sebagai puncak pencapaian yang konon membawa kebahagiaan. Kita tumbuh dalam budaya yang menyanjung mereka yang “berhasil”, meski meraihnya dengan menghalalkan segala cara.
“Kesuksesan materi seolah menjadi jaminan atas kebahagiaan. Namun benarkah demikian? Ataukah justru keberhasilan itu memicu ketakpuasan yang tak kunjung selesai?”
Pertanyaan ini makin relevan saat kita menyaksikan kenyataan bahwa tak sedikit orang yang telah memiliki semua atribut kesuksesan, namun tetap merasa hampa, terus bekerja tanpa henti, bahkan kehilangan makna hidup di tengah limpahan pencapaian.
Sementara di sisi lain, ada yang hidup sederhana, jauh dari sorotan dan gemerlap, namun menjalani hari-harinya dengan tenang, damai, dan penuh syukur. Fenomena ini menggugah perenungan: “Apakah ukuran sukses yang selama ini kita kejar sungguh sanggup memenuhi kebutuhan terdalam manusia akan kebahagiaan?”
Bahagia Tak Usah Dikejar, Namun Dirasakan
Jonathan David Haidt, dalam The Happiness Hypothesis, menjelaskan bahwa otak manusia bekerja dalam pola yang disebut ‘hedonic treadmill’. Ketika kita mencapai sesuatu, kita memang merasa senang. Namun, kebahagiaan itu cepat mereda karena otak kita segera beradaptasi dengan kondisi baru. Maka, standar pun naik, dan kita merasa harus meraih lebih lagi untuk bisa bahagia.
Jonathan Haidt menulis: “once we’re out of poverty …, people get “once we’re out of poverty …, people get stuck on a ‘hedonic treadmill’: their expectations rise …, and the happiness they seek remains constantly just out of reach.” (Haidt, 2006). (“begitu kita keluar dari kemiskinan, orang-orang terjebak dalam ‘hedonic treadmill’: ekspektasi mereka meningkat, dan kebahagiaan yang mereka cari tetap berada di luar jangkauan.”).
Kita terus berlari, mengejar penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, pengakuan yang lebih luas, namun jarang berhenti untuk benar-benar menikmati capaian yang ada. Kepuasan menjadi semu, dan kebahagiaan berubah menjadi ilusi yang selalu tampak lebih jauh di depan.
Pada bagian lain, Haidt juga menulis: “We are all stuck on what has been called the ‘hedonic treadmill.’ You work hard to achieve something—say, a promotion—and when you get it, you’re happy for a little while. But soon, you adapt and want more.”
Yah, parafrase secara bebasnya, kita semua terjebak dalam apa yang disebut ‘hedonic treadmill’. Kita bekerja keras untuk mencapai sesuatu, misalnya, promosi, dan ketika kita mendapatkannya, kita bahagia untuk sementara waktu. Namun, tak lama kemudian, kita beradaptasi dan menginginkan lebih.
Bahagia Tak Butuh Panggung
Berbeda dengan sukses yang cenderung bersifat eksternal, kebahagiaan justru tumbuh dari dalam. Ia muncul saat kita berdamai dengan hidup, menerima ketidaksempurnaan, merasa cukup (meski ‘cukup’ itu relatif sifatnya bagi setiap individu), bersyukur, dan mampu melihat keindahan dalam hal-hal yang sederhana.
Bahagia bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, namun seberapa dalam kita menghargai yang telah ada. Ia tumbuh dari relasi yang tulus, berkat dari rasa cukup, dari kesadaran bahwa arti atau makna hidup tak bisa diukur dengan materi.
Masalahnya, banyak dari kita mengejar sesuatu bukan karena hal itu penting bagi suapan jiwanya, namun karena takut tertinggal dari yang lain. Kita ingin tampak berhasil, sehingga muncul perasaan tak utuh. Di balik pencapaian yang menyilau, acapkali tersembunyi kekosongan dan kehilangan arah.
Mental Korupsi
Namun bagaimana bila kegagalan memahami makna “cukup” tak hanya merugikan pribadi, melainkan merusak kepercayaan publik, dan merobohkan sendi-sendi kepentingan bangsa?
Secara makro, pola hidup dalam ‘hedonic treadmill’ ini juga menjangkiti para oknum pejabat koruptor. Tak cukup jabatan, pengaruh besar, dan gaji besar yang mereka miliki, namun masih saja mereka mencari lebih. Lebih kuasa, lebih pengaruh besar lagi, dan lebih banyak harta yang ditumpuk, tak peduli apa pun caranya. Halalkan segala cara.
Setelah duduk di posisi strategis dan menikmati fasilitas negara, mereka tidak berhenti di situ. Ketika rasa cukup tak pernah hadir, keserakahan menjelma menjadi kerakusan. Uang diraup dari proyek fiktif, suap, gratifikasi, hingga manipulasi anggaran. Mereka menipu rakyat demi memuaskan hasrat pribadi yang tak pernah benar-benar selesai.
Pengejaran ini tidak hanya mencemari nurani, namun juga menghancurkan kepercayaan. Ketika amanah dijadikan komoditas, yang dikorbankan bukan hanya integritas pribadi, namun juga harapan jutaan rakyat yang seharusnya mereka dilayani. Sementara lembaga yang berwenang dan lembaga pengadil tumbuh makin kerdil saja. Adil tak menjangkau rakyat kecil.
Temukan Makna, bukan Kejar Ilusi
Pada akhirnya, sukses yang diraih lewat jalan curang dan culas hanya membuahkan kekosongan dan ketakutan. Sebab, sebagaimana yang diungkapkan Jonathan Haidt, kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian yang tak berujung, melainkan dari kedalaman jiwa yang tahu kapan harus berhenti, merasa cukup, bersyukur, dan bertanggung jawab.
“Hidup bukan soal seberapa jauh kita berlari mengejar mimpi, namun apakah kita tahu ke mana arah kita berjalan. Dan jika pengadilan sejati tak ada di negeri ini, namun di akhirat kelak pengadilan dari Maha Pengadil akan menanti.”
Referensi:
Haidt, Jonathan. 2006. The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. New York: Basic Books.